Howdy, Stranger!
It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!
Quick Links
Categories
- 31.1K All Categories
- 24.4K BoyzLife!
- 5.5K BoyzStyle
- 1.9K BoyzStories
- 5K BoyzLove
- 5.9K BoyzRoom
- 2 *Members Only!
- 1 BoyzAlbum*
- 1 BoyzChat*
- 12.8K BoyzConnect!
- 6K Jabodetabek
- 3.9K Jawa
- 2.5K Nusantara
- 451 International
- 291 BoyzForum Info
- 8 Apa Itu BoyzForum?
Selamat datang di situs Boyzforum yang diarsipkan oleh Queer Indonesia Archive. Forum untuk komunitas gay Indonesia yang populer ini didirikan pada tahun 2003, dan ditutup pada tanggal 15 Desember 2020.
Forum ini diabadikan untuk kepentingan sejarah. Tidak akan ada konten baru di forum ini. Silakan menikmati forum ini sebagai potongan dari sejarah queer Indonesia.
Forum ini diabadikan untuk kepentingan sejarah. Tidak akan ada konten baru di forum ini. Silakan menikmati forum ini sebagai potongan dari sejarah queer Indonesia.
Rembang Petang
Salam teman-teman BF-ku!
Buat menambah koleksi cerita di forum BF tercinta ini, aku akan menyumbang satu buah karya kecilku lagi. Judulnya adalah Rembang
Petang—atau dalam Bahasa Inggris, itu disebut dengan Twilight.
Wah, kok kayak judul novel roman termasyur karya Stephenie Meyer, apa ini cerita tentang vampir? Bukan temanku, bukan. Sama sekali
bukan. Kalian akan tepuk jidat jika membaca karya kecilku ini lantaran sangat bertolak belakang dengan apa yang kalian bayangkan.
Tapi anu..., sebelum teman-teman mulai membaca karya kecilku ini, aku ingin mengenakan tarif buat teman-teman semua sebagai simbol apresiasi buatku penulis amatiran ini. Berapa tarifnya? Murah kok, liat rincian di bawah:
1. Baca cerita ku, boleh bayar dengan 1 ‘Like’ atau 1 ‘LOL’
2. Atau dalam beberapa kasus tertentu, abang bisa membayarnya dengan 1 ‘Kesal’ (sedih...)
3. Kasih Obi 1 komentar (kalau perlu).
Itu aja deh, selamat membaca ya teman-temanku semua. Tetep sehat dan tetep jaga harak selama pandemi yaah (❀*´ `*).
.Prolog.
Aku rasa ini sudah pagi ketika aku bangun dan sadar bahwa ini masih di dalam ruang inap salah satu rumah sakit di kotaku. Seperti de javu, ketika aku melewatkan satu lagi malam berhargaku di sini dengannya satu dekade lalu. Menggelikan sekali. Sebagai mahasiswa semester 7 yang sedang mengejar acc Bab II untuk skripsiku, aku malah lalai dengan kondisiku. Aku lupa batasan pada diriku dan pingsan di tempatku sedang duduk terakhir kali: di ruang kerja pribadi ayahku, terkulai tak berdaya di sana, aku rasa.
Itu terjadi kemarin sore, sepulang dari bimbingan untuk Bab II-ku yang sebelumnya mendapatkan coretan merah di sana-sini. Uh, itu adalah revisi keduaku yang diberikan oleh dosen pembimbingku yang ironisnya, beliau adalah seorang dokter yang juga bekerja di rumah sakit ini. Lima puluh lembar cetakan lebih yang sia-sia setengahnya.
Mendapatkan dosen pembimbing yang juga mempunyai gelar profesor sepertinya sudah tertulis jauh-jauh masa di dalam luhmahful milikku. Sedikit celah atau kelemahan ada pada landasan teori yang aku ajukan, mampu menjadi ancaman fatal bagi kesuksesan acc Bab II-ku.
Namun, lupakan saja itu. Aku kelelahan dan pingsan, itulah yang terjadi hingga akhirnya aku bisa berakhir di tempat ini. Dan ingatan tentang kenangan satu dasawarsa yang dulu pernah terjadi, itu yang akan menjadi inti dari jalan cerita ini.
Kupandangi setiap sisi dinding ruangan ini yang mampu terlihat olehku. Seperti sedang bernostalgia. Di dalam satu ruangan berukuran 5x10 meter ini, masih tersusun rapi dua ranjang inap dengan masing-masing tirai yang menjadi sekat antara ranjang satu dengan ranjang sebelahnya—membuatnya mendapat predikat gagal total jika tujuannya adalah untuk memberikan privasi antar pasien, karena di ruangan kecil ini, aku masih bisa mendengar suara jikalau ada orang yang dirawat di samping ranjang inapku.
Hanya ada satu jendela yang terletak di ujung ruangan ini, mungkin itu tidak akan pernah terbuka lagi—mengingat ruangan ini sekarang berpendingin udara, dan aku senang karenanya. Ah, kesenangan yang ironis, aku rasa.
Selain tambahan pendingin udara tadi, ruangan ini tidak banyak mengalami perubahan, begitu menurutku. Jikalau ada perubahan, itu hanyalah tirai penutup antar ranjang yang sekarang bermotif daun-daun suplir berwarna hijau muda dengan warna dasar kain yang putih bersih, dan ukuran televisinya yang lebih besar dengan model terbaru—jika dua tahun lalu masih bisa dibilang keluaran terbaru.
Aroma ruangan ini pun masih sama—bau sterilizer Detol yang membakar hidungku, pengar sekali—aroma-aroma kesehatan itu. Warna catnya pun masih serupa saat terakhir kali aku terpaksa dirawat-inap di sini—toska. Ajaib sekali, tidak ada noda kusamnya sama sekali. Kecuali bekas garisan samar pastel berwarna biru donker di atas nakas dua laci yang berada di samping tempatku berbaring. Tidak adakah yang berusaha membersihkannya selama kurun waktu sepuluh tahun ini? Coretan pastel itu seakan-akan membelah tombol bel pemanggil yang terhubung di ruangan perawat yang letaknya di ujung koridor ruangan ini. Adanya coretan itu jugalah yang memberiku kesimpulan bahwa ruangan ini belum pernah di cat ulang sama sekali.
Tidak disangka, aku terbaring lemas di tempat yang sama, pun ranjang yang sama pula…
Kuambil dan kubuka satu lembar halaman novelku yang tergeletak di atas nakas kecil. Entah Dad atau Mom yang membawakannya untukku, aku tidak tahu.
Aku tersenyum masam melihat novel ini, sudah genap satu dekade berlalu semenjak hari itu, aku rasa. Minatku untuk membaca langsung surut. Kusibak tirai bermotif daun suplir dari tempatku setengah berbaring agar aku bisa melihat ke seluruh bagian ruangan. Kudapati ranjang sebelah tampak lenggang, rupanya belum ada pasiennya sama sekali di ruangan ini kecuali diriku.
Kutatap ranjang itu—mengabaikan novel roman yang sudah setengah jalan aku baca sebelumnya di rumah. Biarlah, aku sudah hafal sisa jalan ceritanya, sebenarnya. Selama kurun waktu sepuluh tahun ini, aku sudah membacanya sebanyak 7 kali—membuat sampul depan novel ini menjadi lebih kumal karenanya. Ini yang kedelapan. Aku baca ulang, kali ini karena aku memang membutuhkan diversi di sela-sela skripsiku. Tentunya kalian yang sudah menginjak semester akhir di tingkat kuliah tahu sendiri, bukan? Mengajukan proposal dan menulis bab-bab skripsi akan menjadi tantangan tersendiri jika kita tahu ada ancaman revisi ke depannya. Kita membutuhkan sebuah diversi. Untukku, membaca novel menjadi pilihanku.
Sekali lagi kutatap ranjang yang ada di sampingku. Ranjang itu tampak rapi. Tampak bersih dengan sprei barunya. Seberkas sinar matahari yang menembus kaca jendela tampak menyinari bagian atas ranjang kasur tersebut. Terima kasih kepada pendingin udara karena telah menyaring debu yang ada di dalam ruangan ini—menjadikan cahaya itu terlihat murni tanpa sedikitpun noktah padanya. Aku rasa itu sebabnya tanaman Lidah Mertua yang bertugas menyaring udara di dalam ruangan yang dulu berada di pojokan, kini tergantikan dengan tanaman suplir.
Senyum masamku memudar, mendayu seiring kepalaku yang memutar ulang sepotong episode yang terjadi sepuluh tahun lalu di sini, di ruangan ini.
“Wah, wah! Itukah engkau? Lihat! Lihat siapa yang kembali terbaring di sini jika bukan engkau, Shann? Ya Tuhan, sudah besar rupanya engkau, Nak?” seru seorang suster berseragam putih yang samar-samar aku ingat siapa namanya, dan tentu saja ia mengagetkanku. Ia memasuki ruang inap dengan membawa troli berisi bermangkuk-mangkuk menu sarapan. Terdapat paper board yang diapit di sela-sela ketiaknya. Bibirnya menyunggingkan senyum sumringah ketika melihatku terbaring di atas ranjang. Setelah meletakkan paper board di sisi troli, ia berkacak pinggang dan bergeleng-geleng kepala, senyumnya makin melebar.
Kukembangkan senyumku kembali. Bukan senyum masam tentunya. Lihatlah, tidak banyak perubahan selama kurun waktu satu dekade ini kepada dirinya. Hanya terdapat beberapa tambahan kerutan di kening tanda penuaan di sana sini. Dan ijinkan aku untuk tidak membahas hal itu di depannya. Tidak akan pernah lagi, begitu paling tidak. Aku rasa sekarang ia sudah berumur tiga puluh lima.
“Oh hebat! Engkau masih hidup rupanya, Suster Florentina. Dari puluhan perawat yang berada di sini, kenapa harus engkau jualah yang datang? Di mana Suster Jennifer?” protesku sembari meletakkan novel roman di atas dadaku yang sempat aku abaikan.
“Dasar engkau! Sifat burukmu masih saja tidak berubah. Mulutmu masih tidak punya tata krama rupanya,” katanya sembari menoyor kepalaku. Mengingat aku pasien yang sedang sakit, itu bukanlah hal yang patut dilakukan oleh seorang perawat. Aku mengabaikannya—ia hanya kangen kepadaku, itu saja. “Twilight lagi? Oh ayolah, roman? Engkau bercanda, Shann?” cercanya sambil memegang sampul novel yang terbaring di atas dadaku. Baginya, itu adalah hal yang mengejutkan.
“Ah diamlah, Suster Florentina! Saat ini aku sedang tidak ingin mendengar komentarmu,” kataku sambil mengerucutkan bibirku.
“Baiklah, baiklah. Ada apalagi sekarang? Mengapa engkau sampai tumbang lagi? Apakah penyakit lamamu muncul kembali, Shann?” tanya Suster Florentina sambil menaikkan sebelah alisnya.
“Oh bukan, bukan!” tukasku. “Hanya hal sepele, Suster. Aku hanya terlalu lelah saja dengan kuliahku. Skripsi, kau tahu?” kataku mencoba bersombong ria di depannya.
Suster Florentina memutar bola matanya, “Bisa kuliah juga ternyata, anak ini,” cibirnya.
“Hmmph,” dengusku. “Aku ‘kan tidak bodoh-bodoh amat!” kesalku kepadanya.
“Suntikan vitamin, Shann? Atau hanya cukup dengan beberapa tablet saja?” tawar Suster Florentina seraya membaca selembar kertas hasil diagnosa pada paper board-nya. Tentu saja ia menyeringai.
“Ergh,” erangku. Keduanya adalah musuhku. Aku tidak bisa menerima keduanya: suntikan dan tablet. Aku takut jarum. Aku juga kesulitan menelan obat dalam bentuk tablet. Dan Suster Florentina tahu itu. “Tablet, tolong,” kataku memberitahukan pilihan finalku kepadanya. “Dalam bentuk serbuk, tentunya,” cengirku.
“Aku sudah tahu itu, Shann,” Suster Florentina mencebik. “Engkau sama sekali tidak berubah, Shann,” tambahnya seraya manggut-manggut. Ia memandangiku lamat-lamat. Lalu beralih ke ranjang sebelah yang tampak lenggang. Sorot kedua matanya menjadi sendu seketika. “Apa engkau sering menengoknya, Shann…, anak itu?”
Kudenguskan nafasku sekali sebelum menjawab pertanyaan darinya. “Selalu…” kataku dengan senyum yang kembali masam. “Selama sepuluh tahun ini…, setiap akhir bulannya…”
“Itu bagus sekali, Shann…” dayunya, masih menatap ranjang kosong yang berada di samping ranjangku. “Ia anak yang baik, Shann…, kau tahu itu, bukan?” tanyanya.
“Yang terbaik,” kataku.
Kualihkan pandanganku ke arah ranjang yang sama. Sayup-sayup, suaranya terdengar kembali di kedua telingaku. Aku akan menceritakannya kepada kalian. Meski…, itu adalah sepuluh tahun yang lalu…
.
.
.
.
.
[Bersambung.]
Buat menambah koleksi cerita di forum BF tercinta ini, aku akan menyumbang satu buah karya kecilku lagi. Judulnya adalah Rembang
Petang—atau dalam Bahasa Inggris, itu disebut dengan Twilight.
Wah, kok kayak judul novel roman termasyur karya Stephenie Meyer, apa ini cerita tentang vampir? Bukan temanku, bukan. Sama sekali
bukan. Kalian akan tepuk jidat jika membaca karya kecilku ini lantaran sangat bertolak belakang dengan apa yang kalian bayangkan.
Tapi anu..., sebelum teman-teman mulai membaca karya kecilku ini, aku ingin mengenakan tarif buat teman-teman semua sebagai simbol apresiasi buatku penulis amatiran ini. Berapa tarifnya? Murah kok, liat rincian di bawah:
1. Baca cerita ku, boleh bayar dengan 1 ‘Like’ atau 1 ‘LOL’
2. Atau dalam beberapa kasus tertentu, abang bisa membayarnya dengan 1 ‘Kesal’ (sedih...)
3. Kasih Obi 1 komentar (kalau perlu).
Itu aja deh, selamat membaca ya teman-temanku semua. Tetep sehat dan tetep jaga harak selama pandemi yaah (❀*´ `*).
.Prolog.
Aku rasa ini sudah pagi ketika aku bangun dan sadar bahwa ini masih di dalam ruang inap salah satu rumah sakit di kotaku. Seperti de javu, ketika aku melewatkan satu lagi malam berhargaku di sini dengannya satu dekade lalu. Menggelikan sekali. Sebagai mahasiswa semester 7 yang sedang mengejar acc Bab II untuk skripsiku, aku malah lalai dengan kondisiku. Aku lupa batasan pada diriku dan pingsan di tempatku sedang duduk terakhir kali: di ruang kerja pribadi ayahku, terkulai tak berdaya di sana, aku rasa.
Itu terjadi kemarin sore, sepulang dari bimbingan untuk Bab II-ku yang sebelumnya mendapatkan coretan merah di sana-sini. Uh, itu adalah revisi keduaku yang diberikan oleh dosen pembimbingku yang ironisnya, beliau adalah seorang dokter yang juga bekerja di rumah sakit ini. Lima puluh lembar cetakan lebih yang sia-sia setengahnya.
Mendapatkan dosen pembimbing yang juga mempunyai gelar profesor sepertinya sudah tertulis jauh-jauh masa di dalam luhmahful milikku. Sedikit celah atau kelemahan ada pada landasan teori yang aku ajukan, mampu menjadi ancaman fatal bagi kesuksesan acc Bab II-ku.
Namun, lupakan saja itu. Aku kelelahan dan pingsan, itulah yang terjadi hingga akhirnya aku bisa berakhir di tempat ini. Dan ingatan tentang kenangan satu dasawarsa yang dulu pernah terjadi, itu yang akan menjadi inti dari jalan cerita ini.
Kupandangi setiap sisi dinding ruangan ini yang mampu terlihat olehku. Seperti sedang bernostalgia. Di dalam satu ruangan berukuran 5x10 meter ini, masih tersusun rapi dua ranjang inap dengan masing-masing tirai yang menjadi sekat antara ranjang satu dengan ranjang sebelahnya—membuatnya mendapat predikat gagal total jika tujuannya adalah untuk memberikan privasi antar pasien, karena di ruangan kecil ini, aku masih bisa mendengar suara jikalau ada orang yang dirawat di samping ranjang inapku.
Hanya ada satu jendela yang terletak di ujung ruangan ini, mungkin itu tidak akan pernah terbuka lagi—mengingat ruangan ini sekarang berpendingin udara, dan aku senang karenanya. Ah, kesenangan yang ironis, aku rasa.
Selain tambahan pendingin udara tadi, ruangan ini tidak banyak mengalami perubahan, begitu menurutku. Jikalau ada perubahan, itu hanyalah tirai penutup antar ranjang yang sekarang bermotif daun-daun suplir berwarna hijau muda dengan warna dasar kain yang putih bersih, dan ukuran televisinya yang lebih besar dengan model terbaru—jika dua tahun lalu masih bisa dibilang keluaran terbaru.
Aroma ruangan ini pun masih sama—bau sterilizer Detol yang membakar hidungku, pengar sekali—aroma-aroma kesehatan itu. Warna catnya pun masih serupa saat terakhir kali aku terpaksa dirawat-inap di sini—toska. Ajaib sekali, tidak ada noda kusamnya sama sekali. Kecuali bekas garisan samar pastel berwarna biru donker di atas nakas dua laci yang berada di samping tempatku berbaring. Tidak adakah yang berusaha membersihkannya selama kurun waktu sepuluh tahun ini? Coretan pastel itu seakan-akan membelah tombol bel pemanggil yang terhubung di ruangan perawat yang letaknya di ujung koridor ruangan ini. Adanya coretan itu jugalah yang memberiku kesimpulan bahwa ruangan ini belum pernah di cat ulang sama sekali.
Tidak disangka, aku terbaring lemas di tempat yang sama, pun ranjang yang sama pula…
Kuambil dan kubuka satu lembar halaman novelku yang tergeletak di atas nakas kecil. Entah Dad atau Mom yang membawakannya untukku, aku tidak tahu.
Aku tersenyum masam melihat novel ini, sudah genap satu dekade berlalu semenjak hari itu, aku rasa. Minatku untuk membaca langsung surut. Kusibak tirai bermotif daun suplir dari tempatku setengah berbaring agar aku bisa melihat ke seluruh bagian ruangan. Kudapati ranjang sebelah tampak lenggang, rupanya belum ada pasiennya sama sekali di ruangan ini kecuali diriku.
Kutatap ranjang itu—mengabaikan novel roman yang sudah setengah jalan aku baca sebelumnya di rumah. Biarlah, aku sudah hafal sisa jalan ceritanya, sebenarnya. Selama kurun waktu sepuluh tahun ini, aku sudah membacanya sebanyak 7 kali—membuat sampul depan novel ini menjadi lebih kumal karenanya. Ini yang kedelapan. Aku baca ulang, kali ini karena aku memang membutuhkan diversi di sela-sela skripsiku. Tentunya kalian yang sudah menginjak semester akhir di tingkat kuliah tahu sendiri, bukan? Mengajukan proposal dan menulis bab-bab skripsi akan menjadi tantangan tersendiri jika kita tahu ada ancaman revisi ke depannya. Kita membutuhkan sebuah diversi. Untukku, membaca novel menjadi pilihanku.
Sekali lagi kutatap ranjang yang ada di sampingku. Ranjang itu tampak rapi. Tampak bersih dengan sprei barunya. Seberkas sinar matahari yang menembus kaca jendela tampak menyinari bagian atas ranjang kasur tersebut. Terima kasih kepada pendingin udara karena telah menyaring debu yang ada di dalam ruangan ini—menjadikan cahaya itu terlihat murni tanpa sedikitpun noktah padanya. Aku rasa itu sebabnya tanaman Lidah Mertua yang bertugas menyaring udara di dalam ruangan yang dulu berada di pojokan, kini tergantikan dengan tanaman suplir.
Senyum masamku memudar, mendayu seiring kepalaku yang memutar ulang sepotong episode yang terjadi sepuluh tahun lalu di sini, di ruangan ini.
“Wah, wah! Itukah engkau? Lihat! Lihat siapa yang kembali terbaring di sini jika bukan engkau, Shann? Ya Tuhan, sudah besar rupanya engkau, Nak?” seru seorang suster berseragam putih yang samar-samar aku ingat siapa namanya, dan tentu saja ia mengagetkanku. Ia memasuki ruang inap dengan membawa troli berisi bermangkuk-mangkuk menu sarapan. Terdapat paper board yang diapit di sela-sela ketiaknya. Bibirnya menyunggingkan senyum sumringah ketika melihatku terbaring di atas ranjang. Setelah meletakkan paper board di sisi troli, ia berkacak pinggang dan bergeleng-geleng kepala, senyumnya makin melebar.
Kukembangkan senyumku kembali. Bukan senyum masam tentunya. Lihatlah, tidak banyak perubahan selama kurun waktu satu dekade ini kepada dirinya. Hanya terdapat beberapa tambahan kerutan di kening tanda penuaan di sana sini. Dan ijinkan aku untuk tidak membahas hal itu di depannya. Tidak akan pernah lagi, begitu paling tidak. Aku rasa sekarang ia sudah berumur tiga puluh lima.
“Oh hebat! Engkau masih hidup rupanya, Suster Florentina. Dari puluhan perawat yang berada di sini, kenapa harus engkau jualah yang datang? Di mana Suster Jennifer?” protesku sembari meletakkan novel roman di atas dadaku yang sempat aku abaikan.
“Dasar engkau! Sifat burukmu masih saja tidak berubah. Mulutmu masih tidak punya tata krama rupanya,” katanya sembari menoyor kepalaku. Mengingat aku pasien yang sedang sakit, itu bukanlah hal yang patut dilakukan oleh seorang perawat. Aku mengabaikannya—ia hanya kangen kepadaku, itu saja. “Twilight lagi? Oh ayolah, roman? Engkau bercanda, Shann?” cercanya sambil memegang sampul novel yang terbaring di atas dadaku. Baginya, itu adalah hal yang mengejutkan.
“Ah diamlah, Suster Florentina! Saat ini aku sedang tidak ingin mendengar komentarmu,” kataku sambil mengerucutkan bibirku.
“Baiklah, baiklah. Ada apalagi sekarang? Mengapa engkau sampai tumbang lagi? Apakah penyakit lamamu muncul kembali, Shann?” tanya Suster Florentina sambil menaikkan sebelah alisnya.
“Oh bukan, bukan!” tukasku. “Hanya hal sepele, Suster. Aku hanya terlalu lelah saja dengan kuliahku. Skripsi, kau tahu?” kataku mencoba bersombong ria di depannya.
Suster Florentina memutar bola matanya, “Bisa kuliah juga ternyata, anak ini,” cibirnya.
“Hmmph,” dengusku. “Aku ‘kan tidak bodoh-bodoh amat!” kesalku kepadanya.
“Suntikan vitamin, Shann? Atau hanya cukup dengan beberapa tablet saja?” tawar Suster Florentina seraya membaca selembar kertas hasil diagnosa pada paper board-nya. Tentu saja ia menyeringai.
“Ergh,” erangku. Keduanya adalah musuhku. Aku tidak bisa menerima keduanya: suntikan dan tablet. Aku takut jarum. Aku juga kesulitan menelan obat dalam bentuk tablet. Dan Suster Florentina tahu itu. “Tablet, tolong,” kataku memberitahukan pilihan finalku kepadanya. “Dalam bentuk serbuk, tentunya,” cengirku.
“Aku sudah tahu itu, Shann,” Suster Florentina mencebik. “Engkau sama sekali tidak berubah, Shann,” tambahnya seraya manggut-manggut. Ia memandangiku lamat-lamat. Lalu beralih ke ranjang sebelah yang tampak lenggang. Sorot kedua matanya menjadi sendu seketika. “Apa engkau sering menengoknya, Shann…, anak itu?”
Kudenguskan nafasku sekali sebelum menjawab pertanyaan darinya. “Selalu…” kataku dengan senyum yang kembali masam. “Selama sepuluh tahun ini…, setiap akhir bulannya…”
“Itu bagus sekali, Shann…” dayunya, masih menatap ranjang kosong yang berada di samping ranjangku. “Ia anak yang baik, Shann…, kau tahu itu, bukan?” tanyanya.
“Yang terbaik,” kataku.
Kualihkan pandanganku ke arah ranjang yang sama. Sayup-sayup, suaranya terdengar kembali di kedua telingaku. Aku akan menceritakannya kepada kalian. Meski…, itu adalah sepuluh tahun yang lalu…
.
.
.
.
.
[Bersambung.]
Copyright 2021 Queer Indonesia Archive. See our Privacy Policy. Contact us at [email protected]
Dengan menggunakan situs ini berarti Anda setuju dengan Aturan Pakai.
BoyzForum.com adalah situs anti pedofilia!

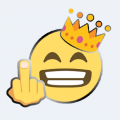
Comments
Jika ada anak kelas 6 sekolah dasar yang menganggap bahwa pelangi itu hidup, maka dialah aku: Shann. Memang begitulah aku, diberkahi imajinasi yang kelewat tinggi sama Tuhan. Pada umurku yang masih terbilang muda, aku berhasil menemukan sendiri teori ala Shann yang mengulas bahwa sebenarnya, pelangi itu adalah hewan berkaki empat. Ia mempunyai sepasang kaki di setiap pangkal dan ujung lengkungan parabolanya. Hebat sekali, bukan? Itu semua adalah gagasan yang aku simpulkan dari bunga mimpi yang aku alami. Berkatnya, aku rasa diriku ini sudah setara dengan Albert Einstein. Paling tidak, begitu menurutku, sih.
Namaku Shannon Raqueza. Kedua orang tua dan teman-teman bermainku biasa memanggilku dengan nama Shann saja, baik di sekolah, maupun di rumah. Tahun ini, aku genap berusia dua belas tahun. Aku bersekolah di sebuah sekolah swasta berbasis internasional—namun bukan itu yang membuatku mahir berbahasa Inggris.
Bisa dibilang, aku ini adalah anak hybrid—anak hasil perkawinan silang dari dua ras unggulan yang berbeda. Jika kalian ingin melihat hasil perkawinan antara Suku Jawa dengan Orang Inggris, maka aku bisa menjadi sampel yang tepat karena Dad Orang Jawa, sedang Mom adalah Orang Inggris—ia lahir di London pada masanya. Dari situlah Tuhan menganugerahkan garis ketampanan khas Eropa pada parasku. Tidak heran jika aku mahir berbahasa Inggris, walau Bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa ibu bagiku.
Di kelasku, Kelas Galaksi Orion, aku terbilang murid paling lemah nomor 3 setelah Rayyen dan Jeff. Itu benar adanya—aku tidak mempunyai daya tahan dan stamina yang bagus. Tapi itu tidak membuatku menjadi bahan rundungan oleh teman-temanku yang lain. Sebaliknya, aku mendominasi kelasku sendiri. Katakan saja, akulah Alpha-nya. Kuakui, alih-alih menjadi bahan rundungan, aku malah menjadi perundung itu sendiri bersama teman-teman sekelasku yang lain. Tentunya, Rayyen dan Jeff lah yang biasanya menjadi sasaran empuk kami.
Namun seperti yang aku katakan tadi, aku tidak dikaruniai daya tahan tubuh dan stamina yang bagus. Perundung yang ironis, tidak jarang, kelinci berlari lebih cepat daripada harimau yang akan memangsanya. Payah memang, aku ini.
Ah aku ceritakan kisah yang menarik. Pernah suatu kali, aku kalah berkelahi dengan Brian—kucing peliharaanku sendiri yang berbulu putih bersih bak saput mega, hanya gara-gara berebut makanan. Brian menubrukku tepat di jidatku—membuatku terhuyung ambruk ke belakang. Aku terpaksa mengibarkan bendera putih di depan Brian.
Dan ergh…, jika mengambil katak lalu menekan perutnya, sehingga membuat keempat kakinya bergerak-gerak, atau mengusik kecoa yang menempel di sebuah tembok dengan menggunakan lidi, itu termasuk ke dalam kriteria pecinta binatang, maka aku demikian. Aku memang selalu tertarik dengan biota yang berada di sekitarku. Pun jika kecoa tadi tiba-tiba terbang, aku akan lari terbirit-birit.
Oh, aku rasa, kuakui aku juga anak yang cengeng. Pernah suatu hari, karena Mom terlalu sibuk di dapur dan tidak ingin aku mengganggunya, ia meminta diriku untuk menonton sebuah film kartun tentang gajah yang diputarkan oleh Mom melalui laptop-nya. Seusai menonton film tersebut, aku buru-buru berlari ke dapur untuk mengecek Mom. Begitu melihatnya, aku menangis sambil kembali berlari memeluk Mom. Hal itu benar-benar membuat Mom kaget dan kebingungan. Setelah ia menanyakan sebabnya, kujawab jika aku menangis karena melihat adegan Dumbo Si Anak Gajah yang harus terpisah dengan induknya. Aku terlalu menganggap serius adegan film itu dan akhirnya terbawa perasaan.
Di keluargaku, aku adalah anak tunggal. Kami adalah keluarga kecil yang bahagia. Dan jika ditanya apakah aku ingin mempunyai seorang adik, maka aku akan menjawab tidak sebagai wujud penolakanku. Bagiku, kami sudah sempurna. Aku juga tidak merasa kesulitan untuk mencari lawan jika hendak bermain tembak-tembakan. Brian bisa menggantikannya untuk menjadi sasaran tembak. Aku rasa ia tidak keberatan—ia pelari yang cukup cepat.
Kedua orang tuaku adalah orang yang sibuk. Dad dan Mom adalah salah satu pemilik tenant restoran keluarga di dua mall lokal sekaligus. Mereka mempekerjakan seorang Nanny untuk membantu menjagaku di rumah. Namun walau begitu, mereka masih tetap menjaga dan mengawasiku, bahkan dengan telik—mengingat aku adalah anak yang hiperaktif. Terutama jika aku mengkonsumsi protein dan glukosa secara berlebihan. Sungguh sifat yang kontras mengingat kondisi tubuhku yang berdaya tahan lemah. Jika mereka tidak merawatku sedemikian rupa atau lalai, aku bisa saja mimisan secara tiba-tiba, dan itu kerap kali terjadi jika aku terlalu lelah.
Ah, sebenarnya mereka tidak lalai juga, sih. Setelik apapun mereka dalam hal mengawasiku, aku memang selalu mempunyai cara untuk mengelabui mereka. Seperti ketika aku dibatas-batasi dalam mengkonsumsi sereal coklat kesukaanku, aku diam-diam mencuri sereal itu barang segenggam-dua genggam untuk aku nikmati secara sembunyi-sembunyi. Dan tentunya mengkonsumsi yang manis-manis secara berlebihan akan membuatku menjadi lebih bertenaga sehingga hiperaktif. Alhasil, kedua orang tuaku heran mendapatiku sudah berada di atas pohon dan harus bersusah-payah menurunkanku dari sana karena aku tidak bisa turun sendirian.
Itu hanya satu kisah lain saja. Di kelasku, Kelas Galaksi Orion, aku terkenal sebagai anak yang sering didapati dalam kondisi mimisan dan bisa pingsan secara tiba-tiba jika aku terlalu memforsir kemampuan tubuhku. Perundung yang payah memang, aku ini.
Tapi aku tidak pernah berkecil hati. Dad dan Mom, bahkan guru-guru yang ada di sekolahku, sepakat mengatakan bahwa aku anak yang cerdas, walau aku memang anak yang bandel juga sebenarnya. Aku mempunyai imajinasi yang lebih tinggi daripada teman-teman sebayaku. Kelewat tinggi malah.
Teori ala Shann yang membahas bahwa pelangi adalah salah satu makhluk hidup tadi, hanyalah salah satunya saja. Masih ada penjabaran yang lebih lanjut lagi tentang teori ciptaanku itu. Sebut saja, teoriku mengalami evolusi.
Sebenarnya, selain warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, pelangi masih memiliki satu warna lagi: hitam. Paling tidak dulunya begitu, sebelum warna-warna yang berada di dalam susunan pelangi itu tidak mau berteman lagi dengan warna hitam dan memutuskan untuk mengusirnya dari kawanan warna-warna legendaris itu. Menurut mereka, hitam itu jelek dan jahat. Paling tidak, itulah yang mereka katakan melalui mimpiku.
Eh, apakah kalian penasaran bagaimana rasa dari pelangi jika kita jilat? Apakah mereka sebenarnya memang mempunyai rasa, mengingat gradasi warna yang dimiliki sangat menarik dan memanjakan mata? Apakah benar mereka itu manis seperti gulali? Tapi aku rasa tidak juga, mengingat mereka adalah makhluk hidup berkaki empat. Dan itu juga yang membuat mereka sulit sekali dikejar. Aku tidak pernah sekalipun mampu menyentuh pelangi, apalagi mencicipinya. Kata ayahku, mereka itu jauh sekali letaknya. Aku tidak pernah berhasil mengejar pelangi di dalam bunga tidurku, sekali pun aku yakin, aku sudah mengenakan tas robot yang mampu memberikan dorongan tenaga sekelas jet untuk bermanuver ria di angkasa. Kuakui, pelangi itu pelari yang jauh lebih tangguh daripada Brian.
Ah, tambahan informasi tentangku, pun jika kalian masih ingin tahu. Selain makanan yang manis, aku memiliki segudang pantangan yang berkaitan erat dengan makanan dan jajanan lainnya. Yakni pantangan pada hasil ternak seperti daging-dagingan, susu, telur, dan keju. Kuliner laut yang memang mengandung protein yang baik pun, masuk ke dalam daftar hitam kedua orang tuaku.
Tentu saja itu bukan pantangan mutlak, aku masih diperbolehkan menikmati semuanya. Hanya saja jika itu masih dalam kalkulasi batas wajar yang disarankan oleh dokter kepada Dad dan Mom. Seperti contohnya, aku sangat menyukai daging ayam yang diolah dalam bentuk sajian apapun. Sayangnya, aku tidak boleh memakan lebih dari 100 gram daging ayam dalam kurun waktu 6 jam. Karena jika itu aku langgar, maka aku akan menjadi hiperaktif, berlari ke sana dan ke sini. Ujung-ujungnya aku kelelahan dan pingsan tentu saja. Sangat retoris.
Itu saja dulu. Aku tidak terlalu ingin menceritakan banyak hal tentang diriku, sebenarnya. Karena nantinya kalian akan mampu menyimpulkan dengan mudah bahwa sebenarnya aku hanyalah anak yang kelewat bandel dan suka mendominasi, walau cerdas dan penuh imajinasi.
.
.
.
.
.
[Bersambung.]
Hiruk-pikuk murid terdengar menggema di setiap lorong kelas. Murid-murid itu, mereka tampak gesit melangkah di atas lantai krem yang terhampar di setiap penjuru ruangan. Semuanya tampak terburu-buru menuju kelas masing-masing sebelum bel tanda dimulainya pelajaran berdering. Lima menit lagi, aku rasa.
Aku berdiri di samping pintu masuk kelas yang setengah bagian atasnya adalah kaca bening. Kubenahi dasi kupu-kupu yang terpasang di kerah seragamku dengan penuh kewibaan. Itu dasi yang bagus, dasi dengan motif kotak-kotak yang mempunyai paduan warna hitam-merah, sangat selaras dengan motif celana seragamku yang memang serupa dan kemeja seragamku yang putih bersih. Itu sangat menambah karismaku. Aku menunggu Rayyen dan Jeff.
Aku tidak sendirian. Darell dan Angelo bersamaku. Mereka berdua adalah temanku yang paling karib. Walau lebih seperti beta dan gamma bagiku—pengekorku yang loyal dan setia. Mereka adalah temanku sejak pertama kali aku menginjakkan kaki di sekolah internasional ini. Kami tidak terpisahkan, kecuali salah satu dari kami jatuh sakit lalu meminta absen.
Darell adalah anak periang yang maskulin dan dianugerahi garis wajah khas oriental. Dia memang keturunan asli warga negara tirai bambu—Hongkong lebih tepatnya. Kulitnya benar-benar putih dan tanpa cela—salah satu hal yang membuatku merasa iri kepadanya. Akan sangat cocok jika ia dikontrak untuk iklan produk sabun pemutih anak-anak—jika memang sabun seperti itu ada. Tinggi badan Darell sama dengan tinggi badanku: 145 centimeter. Tinggi badan yang sempurna untuk dimiliki anak kelas 6 seperti kami. Itu sangat membantu kami untuk mendominasi antar kelompok yang memang ada di sekolah kami.
Sedang Angelo, ia adalah bocah hybrid sepertiku. Hanya saja, bukan ibunya yang berketurunan Inggris asli, melainkan ayahnya. Sayangnya, walau tampan sepertiku, ia tidak lebih tinggi dariku dan Darell—membuatnya menjadi gamma di dalam kelompok kami secara otomatis.
Kedua orang tua mereka menetap di Indonesia untuk peruntungan nasib, yang memang berhasil sebenarnya. Ayah Darell adalah seorang importir barang dari Cina, membuatnya menjadi pengusaha sukses di bisnisnya karena mendapatkan barang murah yang dijual mahal di negara ini.
Ikatan di dalam kelompok kami sangat kuat. Terlebih, kedua orang tua kami sudah saling mengenal satu sama lain dan bahkan saling bermitra bisnis. Selain itu, kami juga banyak mempunyai kesamaan: kami sama-sama tidak suka makan sayur. Itu salah satunya.
Di dalam kelompok, kami saling mendukung satu sama lain. Perbedaan pendapat bukanlah halangan. Justru malah menjadi bumbu yang menarik untuk memperkuat fraternitas di antara kami masing-masing. Itu adalah ikatan yang kuat. Mungkin karena dari kelas 1, kami sudah terikat satu sama lain.
Dad dan Mom berkata bahwa aku memiliki karakter kepemimpinan. Mungkin karena sifatku yang terlalu kentara untuk selalu menjadi nomor satu. Ambisi yang meluap-luap, mungkin itu komplemen yang tepat untuk menggambarkan karakter diriku. Membuatku disegani oleh anak-anak di dalam kelasku sendiri; Kelas Galaksi Orion. Bahkan konon, di seluruh penjuru sekolah.
Sebenarnya masih ada satu lagi teman karibku selain Darell dan Angelo—Russel namanya, delta pada kelompok kecil kami. Loyalis yang lain. Ia adalah anak baru yang pindah dari New Jersey pada saat kami menginjak jenjang kelas 3 sekolah dasar. Aku tidak tahu persis apa pekerjaan orang tua Russel. Desas-desus yang pernah aku dengar, ayah dan ibunya yang memang asli orang Amerika, menjadi utusan hubungan diplomatis antara Indonesia-Amerika—membuat Russel harus belajar Bahasa Indonesia sedini mungkin, bahkan sebelum kepindahannya kemari.
Walau Russel termasuk anak baru di kelompok kecil kami, ia benar-benar sukses memerankan perannya sebagai loyalis yang lain di hadapan kami. Hanya saja dia tidak pernah berselera untuk ikut andil jika aku, Darell, dan Angelo akan merundung sasaran empuk kami seperti pagi ini.
Kami memang kelompok kecil, tapi kami sangat mendominasi, terlebih di kelas kami sendiri. Tidak ada yang berani menyanggah apapun keinginan kami, keinginanku. Jika kami sudah meminta, maka mereka wajib memberikannya kepada kami. Di bawah kepemimpinanku, kelompok kecil kami termanajemeni dengan baik. Kami bahkan mempunyai motto: apa yang memang menjadi kepunyaan mereka, maka adalah kepunyaan kami juga, sedang apa yang menjadi kepunyaan kami, maka tetap seperti itu. Tidak dapat diganggu gugat. Kami adalah kelompok yang paling disegani. Tentu saja karena ada aku yang karismatik di dalamnya. Titik.
“Kira-kira, apa yang Jeff dan Rayyen bawa untuk bekal hari ini?” tanyaku kepada Darell dan Angelo.
“Kemungkinan besar Jeff akan membawa fillet Ikan Salem lagi, semalam aku memata-matai ibunya Jeff. Ia membelinya dari toko,” sahut Angelo. Wajar jika Angelo sampai tahu. Aku beritahu kalian, kedua orang tuanya menjalankan toko grosir sayur dan daging-dagingan terbesar di kota kami. Dad dan Mom bahkan menjadi pelanggan tetap toko mereka. Dua restoran keluarga kami memang mengandalkan bahan-bahan segar dari toko grosir sayur milik keluarga Angelo. Sama seperti ayah Darell, kedua orang tua Angelo juga bisa dikatakan sukses dalam bisnisnya.
Aku memutar bola mataku, “Ugh, berarti aku tidak bisa menikmatinya lagi kali ini,”
“Tenang, Shann! Aku berani bertaruh, Rayyen akan membawa burger jamur lagi untukmu,” tukas Darell. Ia cengar-cengir.
“Wuek. Aku tidak pernah berselera memakan itu,” tukasku seraya berpura-pura meluah di hadapan Darell. “Jamur. Bagus sekali,” cemoohku.
“Lihat, siapa yang datang!” Angelo menunjuk sosok Jeff yang sedang berjalan di ujung lorong. Kedua matanya menangkap pandangan kami dengan was-was begitu ia mendapati keberadaan kami di depan pintu masuk kelas. Kami menyeringai. Jeff berjalan dengan ragu ke arah kami. Bisa kami lihat, langkahnya semakin pelan ketika ia hampir mendekati pintu kelas di mana kami berdiri dengan melipat kedua tangan kami. Seperti biasa, ia menenteng tas bekalnya.
“Hei, domba lugu! Apa yang engkau bawa pagi ini untuk kami?” tanyaku. Bossy. “Perlihatkan isi kotak bekalmu,” pintaku sambil menyeringai.
“Ah, ayolah, Shann. Tidak lagi, ingat? Kau sudah berjanji,” erangnya.
“Itu ‘kan kemarin,” tukasku seraya menaik-turunkan kedua alisku. Aku tidak menerima kata tidak. “Darell,” kataku sambil menunjuk tas bekal milik Jeff dengan daguku.
Dengan cekatan Darell mengambil kotak bekal Jeff dari tas bekalnya. Jeff tidak berkutik di hadapan kami. Ia sudah tahu akibatnya jika bertentangan pendapat dengan kelompok kami, atau ia akan kembali terkunci di loker miliknya.
Darell membuka kotak bekal tersebut, “Waduh, ini sih brokoli semua,” seru Darell seraya menunjukkan isi kotak bekal tersebut kepada kami—brokoli rebus. Sontak kami mendengus. Tidak ada yang pernah menyukai sayur satu itu di antara kami. Terlalu hijau menurutku. Dan itu bukan pertanda yang baik untuk dimakan. Kimia beracun sering kali diberi label hijau, bukan? Imajinasiku mengatakan bahwa brokoli itu toksik.
Darell mengembalikan kotak bekal itu kepada Jeff.
“Kau ini sedang diet atau apa?” tanyaku kesal seraya mendorongnya agar ia segera masuk ke dalam kelas, lenyap dari pandangan kami.
“Hari keberuntungan Jeff, eh?” cengir Angelo.
“Tebakanmu meleset jauh, Angelo. Itu bukan Ikan Salem seperti penuturanmu,” kataku.
“Sudah menjadi menu makan malamnya terlebih dahulu, barangkali begitu?” tukas Angelo seraya mengangkat bahunya. Aku memutar kedua bola mataku kembali.
“Hah! Brokoli, ia tahu kita tidak pernah suka itu, bukan? Terlebih, ia terlalu hijau. Tentu saja sangat toksik,” keluhku seraya melipat kedua tanganku di dada.
“Aku setuju jika Jeff tahu bahwa kita membenci brokoli. Tapi…, toksik, Shann? Engkau becanda?” kata Darell seraya menaikkan kedua bahunya.
“Aku rasa tidak, Shann. Itu hanya imajinasimu saja,” kata Angelo. “Brokoli itu sehat. Aku tahu itu. Hanya saja aku tidak pernah menyukainya,” tambahnya.
“Hah! Lihat siapa yang bicara. Aku tidak mau dengar itu dari anak penjual sayur, Angelo!” dengusku. Angelo memutar bola matanya.
Bel tanda masuk kelas berbunyi. Kami segera memasuki kelas. Rayyen datang satu menit sebelum guru pelajaran pertama memasuki ruang kelas. Tanpa kami suruh, Rayyen sudah memperlihatkan isi kotak bekalnya. “Ugh!” dengusku. Itu memang burger jamur.
.
.
.
.
.
[Bersambung.]
Terkadang, aku memang abai. Ceroboh. Tidak terkontrol. Nekat. Rapal saja semua sifat itu ke dalam sebungkus kata: liar. Aku kalap. Dan itulah aku, menuai karma langsung. Akan aku ceriterakan kepada kalian.
Di suatu pagi cerah yang lain, aku, Darell, Angelo, dan Russel, duduk di kantin yang masih tampak lenggang. Memang masih terlalu pagi untuk datang kemari karena biasanya kantin akan ramai pada saat jam istirahat saja. Menu yang disediakan pada pagi hari masih sedikit yang siap—hanya minuman instan hangat seperti susu, Ovaltine, Milo, atau minuman lainnya yang mengandung malt. Masing-masing dari kami memesan minuman hangat itu. Russel yang membayar, tentu saja.
Angelo mengeluarkan beberapa buah granola bar coklat yang cukup untuk kita. Ia mengambil mereka secara cuma-cuma dari toko grosir sayur milik orang tuanya. Aku langsung saja menyambar satu. Tidak setiap hari aku bisa menikmati kudapan ini. Coklat, kau tahu?
“Tidak salah engkau, Shann? Ini mengandung banyak gula. Engkau lupa apa yang akan terjadi kepadamu jika engkau memakannya? Bukankah Ovaltine itu saja sudah cukup manis untukmu?” sergah Angelo.
“Masa bodoh dengan itu, Angelo. Tidak ada yang bisa melarangku di sini,” tukasku seraya memutar kedua bola mataku. “Toh, engkau membawakannya sesuai dengan jumlah kami di sini.”
Aku tahu batasanku, aku rasa. Melahap satu batang granola coklat bukanlah suatu masalah menurutku. Pun semalam, diam-diam aku mencuri sereal aneka rasa buah dari lemari kabinet dapur. Aku gemas dengan bentuk bintangnya yang berwarna-warni itu. Dan itu sudah lebih dari 6 jam yang lalu.
“Pastikan bukan kami yang akan menggotongmu ke ruang istirahat lagi. Engkau berat, Shann, tahu itu?” seloroh Darell.
“Ergh, enyahlah saja!” cebikku. Kembali kugigit granola bar itu dengan masa bodoh.
“Sepertinya akan ada lovey-dovey di sini,” kata Russel yang sedari tadi tenang-tenang saja.
“Apa maksudmu, Russ?” tanya Darell seraya mengerutkan keningnya.
“Mari berharap saja kita tidak meluah,” jawab Russel seraya menunjuk seorang anak yang mendatangi kami, dengan dagunya.
“Oh bagus. Apa yang harus aku lakukan?” tanyaku panik.
“Cobalah untuk tetap tenang, Shann,” Darell menyarankan.
“Bagus sekali, Darell! Tentunya itu akan sangat membantu,” sarkasku kepada Darell. Aku membuang napas penat, sekalipun anak itu belum sampai kemari.
Sebenarnya bukan perhatiannya yang berlebihan terhadapku yang membuatku jengah jika berada di dekatnya. Anggap saja ada hal lain yang membuatku demikian. Aku belum ingin memberitahukan kepada kalian. Aku tidak suka ditertawai.
Anak itu berjalan kemari dengan riang. Langkah lebarnya seperti menari-nari di udara—memperlihatkan keanggunannya. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai begitu saja, berayun-ayun lembut mengikuti irama langkahnya yang ringan itu. Dengan senyum berseri, ia menyapa kami semua.
“Pagi kalian!” serunya. Selalu saja, energinya meluap-luap.
“Wah halo, Claire. Selamat pagi untuk Shann lagi?” goda Darell. Claire nyengir. Aku merengut. Kuinjak sepatu Darell. Sayang tidak kena.
Ialah Claire, anak perempuan paling molek jelita di kelas kami. Hits sampai ke kelas-kelas sebelah. Memiliki perangai yang selalu ceria. Ia dianugerahi postur tubuh yang semampai. Lebih tinggi daripada Russel. Ah, tingginya hampir menyamaiku malah. Salah satu dari sekian banyak anak perempuan yang terpesona dengan karismaku, aku rasa. Membuatku selalu menjadi bahan olok-olokkan seisi Kelas Galaksi Orion. Ia anak yang terpandai di kelas kami. Selain itu, ia juga pandai memasak. Tinggi sekali minatnya dalam bidang itu. Terlebih, jika ia melakukannya semata-mata hanya untukku. Dan ergh.., aku rasa, ia juga sama sepertiku—menyukai hewan. Hanya saja…, ah lupakan sejenak.
“Tentu saja!” serunya riang. “Selamat pagi, Shann. Bagaimana tidurmu semalam?” tanya Claire.
“Entahlah, Claire. Bagaimana tidurmu semalam, Darell?” kualihkan pertanyaan itu untuk Darell, tanda bahwa aku sedang tidak ingin jika Claire berada di sekitar kami. Itu akan sangat merepotkanku karena cinta monyet akan selalu menjadi bahan olok-olok sampai kapanpun.
Claire mendengus, memasang raut masam mendengar responku yang terkesan abai. Tapi itu tidak bertahan lama. Raut cerianya muncul kembali seiring ia menjinjing sekotak bekal dan memamerkannya di depan dadanya. Ia menyunggingkan senyum cerianya, “Hari ini aku bawakan engkau fillet ayam, Shann, engkau suka ayam, bukan? Aku tahu itu!” serunya antusias. Kami bisa mendengar nada keranjingan di sana.
“Oh, bagus sekali, Claire!” kata Darell sambil memutar bola matanya.
“Tepat sekali, memang itu yang ia butuhkan sekarang. Benar tidak, Shann?” seloroh Angelo seraya memamerkan giginya.
“Benar. Ia memang suka membunuhku pelan-pelan,” timpalku dengan nada malas.
“Ayolah, Shann. Cicip barang sedikit saja. Aku tahu engkau tidak diperbolehkan menikmati daging ayam lebih dari 100 gram per enam jam,” desak Claire.
Aku terkesiap mendengarnya. Itu sangat memalukan. “Dari mana engkau tahu hal itu?” tanyaku sambil melotot.
“Yah, satu sekolah sudah tahu hal itu, bukan? Itu retoris,” jawab Claire menaikkan kedua bahunya dengan tak acuh.
“Benar. Tentu saja,” dengusku, aku memutar kedua bola mataku.
Ketiga teman-teman kelompokku cekikikan mendengarnya.
“Aku akan meninggalkan kotak bekal ini di sini. Kalian makan saja. Aku yang membuatnya pagi ini. Tentunya masih hangat,” seru Claire girang. “Kembalikan kotak bekalnya jika sudah kosong, ya?” itu suatu paksaan halus darinya untuk menghabiskan isi kotak bekal ini. Ia beranjak kembali menghampiri teman-temannya yang ternyata menunggu di balik pintu kantin dengan langkah ringannya yang anggun.
“Akan kau makan itu, Shann?” tanya Darell.
“Kalian makan sajalah, aku tidak terlalu berselera makan itu pagi ini,” tolakku. Mempertahankan gengsi.
“Tentu, tentu. Kami tidak akan ragu,” kata Angelo seraya membuka kotak bekal itu yang ternyata isinya ada banyak potongan-potongan fillet ayam balut tepung renyah dengan hiasan dua potongan tomat segar. Mereka tampak menggiurkan dengan tambahan bubuk nori yang ditaburkan di sana-sini. “Tentu saja tomatnya akan aku singkirkan, tidak perlu ditanya lagi,” tambah Angelo sambil menyisihkan tomat itu ke pinggir dengan lugu.
Mereka mulai mencomoti satu demi satu potongan fillet ayam itu dan melahapnya dengan penuh kenikmatan seakan-akan baru pertama kali ini mereka mencicipi makanan buatan Claire.
“Wah, Shann. Nikmat benar, seperti biasanya. Ia memang pandai mengolahnya,” puji Darell. “Cobalah satu, engkau tidak akan menyesal. Aku rasa, satu tidak masalah untukmu, bukan?” tanya Darell. Ia mencoba membujukku.
“Itu benar, Shann. Ia sudah susah payah membuatkan ini untukmu. Aku rasa ia bangun lebih pagi dari biasanya untuk membuatkanmu masakan ini. Cobalah, ini enak sekali,” Angelo meyakinkanku.
“Ah baiklah, baiklah! Kalian terlalu cerewet untuk ukuran laki-laki,” cemoohku.
Kuambil satu potongan fillet ayam terkecil dan kumasukkan ke dalam mulutku, semata-mata hanya untuk menghargai usaha Claire. Paling tidak, agar kesan itu ada.
Aku menelannya dalam tujuh kali kunyah. Sialan, mereka tidak salah, ini memang nikmat sekali. “Baiklah, ini tidak terlalu buruk,” kataku, masih tetap mempertahankan gengsi.
“Kenapa engkau tidak menjadikannya pacar saja, Shann. Kalian tampak serasi, menurutku,” goda Darell.
Aku melotot geram. Kukepalkan tinju di depan mukanya.
“Oh ayolah, hanya karena dia seorang kanofili, lantas engkau takut berhubungan dengannya?” tanya Darell.
“Urgh…, engkau tahu aku tidak terlalu suka anjing, bukan?” aku membela diri.
“Baiklah, asal kau tahu, Shann. Claire tidak semenakutkan anjing,” seloroh Darell. “Dan banyak siswa laki-laki yang mengantre untuk menjadikannya pacar,”
Aku memutar kedua bola mataku kembali, malas menanggapi. Aku memang tidak bisa ditolong lagi. Aku memang pecinta binatang. Tapi, selalu ada perkecualian, bukan? Aku tidak terlalu suka anjing. Apapun, kecuali anjing. Dan Claire termasuk ke dalam penggemar berat spesies yang satu itu.
Saat itulah kulihat lima siswa laki-laki berjalan mendatangi kami. Aku familiar dengan mereka. Kelompok kecil lainnya dari kelas sebelah—Kelas Galaksi Sombrero. Berjalan jumawa di garis paling depan, pemimpin mereka: Riley. Kabar burung mengatakan, ia adalah anak seorang pasukan khusus dari negera yang serupa dengan nenek moyang Russel—Amerika. Sedang ibunya, adalah Warga Negara Indonesia asli. Bisa dikatakan, ia bocah hybrid sama seperti aku dan Angelo.
Riley memiliki postur tubuh yang gempal. Tinggi badannya menyamaiku dan Darell. Berat badan Riley melebihi berat badan kami berdua. Dari dulu, badan Riley selalu terlihat lebih gempal dibandingkan dengan semua murid yang ada di sini. Terlalu banyak makan babi, aku rasa.
Seperti aku, ia memimpin sebuah kelompok kecil perundung di kelasnya sendiri. Sedari dulu, kami tidak pernah bertegur sapa. Setiap berpapasan, kami bermuka masam satu sama lain. Menandakan ketidaksukaan di antara kami.
Sedikit informasi, kelas kami memang tidak pernah akur dengan Kelas Galaksi Sombrero yang berada di bawah kepemimpinan Riley. Dan karena keuntungan Riley yang berbadan besar, semenjak kelas 4 sekolah dasar, kelas kami membangun aliansi dengan kelas sebelah lainnya—Kelas Galaksi Andromeda yang dipimpin oleh anak periang bernama Mark. Aku tidak akan menceritakan siapa Mark di sini. Hanya kameo tidak penting. Itu saja.
Ketidakakuran kelas kami dengan kelas milik Riley bukanlah tanpa alasan. Kelompok kecil kami memang telah melebarkan sayap dengan kelas milik Mark. Aku sebagai anak yang memiliki ambisi yang besar, ingin lebih melebarkan kepemimpinanku dengan mencoba merambah ke kelas sebelah lainnya—Kelas Galaksi Centaurus, kelas terakhir tanpa kelompok perundung kecil seperti kami. Ah, bisa dikatakan, itu adalah kelas netral, kelas tanpa pemimpin.
Sesuatu yang semakin besar tentunya akan bersinggungan dengan sesuatu yang lain pula. Karena untuk sampai di titik puncak, hanya diperlukan satu kelompok saja yang mendominasi. Hanya boleh ada satu pemenang di podium puncak. Celakanya, Riley dan aku memiliki ambisi yang sama—mengambil alih Kelas Galaksi Centaurus dan tiba di posisi puncak. Oleh sebab itulah, kelas kami tidak pernah akur sedari dulu—membuat Kelas Galaksi Centaurus masih terbebas dari aliansi manapun sampai sekarang.
Riley dan antek-anteknya berhenti di sebelah meja kami. Darell, Angelo, dan Russel berdiri bersiaga. Melihat Riley berada dekat dengan kami seperti ini, bukanlah pemandangan yang bisa dilihat setiap hari. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah 6 tahun kami bersekolah di sekolah internasional ini. Aku tetap duduk tenang sambil melipat kedua tanganku di dada. Memasang tampang yang penuh kewibaan seorang pemimpin—yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar tentunya.
“Wah wah, coba tebak siapa yang mengunjungi kami?” celetuk Darell.
“Apa permainanmu kali ini, Riley Cyrus?” tanya Angelo.
“Aku tidak ada perlu dengan kalian, aku ada perlu dengannya,” jawab Riley sambil menunjukku dengan jari telunjuknya.
“Atas keperluan apa?” tanya Russel, ia memasang badan di depan Angelo.
“Jauhi Claire, dia milikku seorang,” katanya tak acuh.
Aku terkesiap. Kupasang senyum menyeringai. Masalah perempuan ternyata. Aku memang tidak tertarik dengan Claire. Dia saja yang terlalu antusias denganku. Ambivalensi—aku tidak membenci Claire, tapi aku tidak suka dengannya karena ia anak yang kanofilia. Aku tidak suka perempuan yang menyukai hal yang paling aku tidak sukai—anjing peliharaan.
Akan tetapi, motto kelas kami itu merupakan harga mati—apa yang menjadi kepunyaan kami, maka tetap seperti itu. Claire duduk di Kelas Galaksi Orion, kelas kami, maka ia akan tetap seperti itu apa adanya.
“Itu tidak mungkin, tubuh gempal, engkau tahu aturannya,” kataku sambil masih duduk dengan segala kewibawaan yang ada pada diriku.
“Apa kau bilang?!” gertak Riley.
“Engkau mendengarnya dengan jelas, tubuh gempal,” jawabku tenang sambil menyeringai.
“Kau berani meledekku, Shann?!” Riley mengepalkan kedua tangannya. Darell dan Angelo membusungkan dadanya. Russel mundur selangkah di belakang Angelo. Keempat antek Riley juga tampak siaga—merasa was-was dengan apa yang akan terjadi. “Kuulangi sekali lagi, jauhi Claire. Dia milikku!” kata Riley geram.
“Kenapa engkau memintanya kepadaku seakan-akan aku adalah selingkuhannya, Riley? Engkau tahu aku tidak akan merendahkan diriku, bukan? Atau engkau sengaja mencari masalah di hadapanku?” tanyaku penasaran.
“Jangan berlagak bodoh, Shann. Aku mencium informasi bahwa Claire telah berhubungan dekat denganmu. Dan itu benar adanya, aku melihatnya sendiri pagi ini dengan kedua mataku, engkau memaksanya memberikan makanan kepada kelompokmu, ‘kan?” gertak Riley.
“Sepertinya engkau salah, Guk,” gonggongku kepada Riley. “Ia sendiri yang membuatkannya untuk kami, ah, untukku lebih tepatnya,” kataku seraya mengelus manja kotak bekal milik Claire dengan ujung jari telunjukku. “Ia tergila-gila padaku, Guk. Kau tahu itu?” aku memberi penekanan pada gonggonganku untuk Riley. “Tapi itu tetap tidak mengubah fakta bahwa kami tidak bisa membiarkan Claire berhubungan dengan anjing yang suka mengendus informasi sepertimu,” kataku seraya menyeringai.
Kutatap Riley dengan tajam. Darell, Angelo, dan Russel, tampak tersenyum puas mendengar aku tidak akan membiarkan Claire berhubungan dekat dengan Riley. Aku akan membonggoli mereka satu per satu jika ini sudah selesai. Mereka menjadi menyebalkan jika mendengar nama Claire keluar dari mulutku.
“Anak sialan!” raung Riley seraya menendang meja kantin yang ada di depanku—membuat kotak bekal milik Claire terguncang dan menghamburkan isinya kemana-mana. Hal itu membuatku berang. Aku berdiri dengan gagah dari dudukku. Tapi Riley yang berbadan besar itu ternyata terlalu pengecut, ia kabur bersama dengan antek-anteknya sebelum aku sempat memakinya.
“Kejar!” pintaku kepada Darell, Angelo, dan Russel.
Kami berhamburan berlari keluar dari pintu kantin menuju lorong sekolah di mana Riley dan antek-anteknya kabur tunggang-langgang. Kami berlari gesit menghindari murid-murid yang sedang berjalan di lorong-lorong kelas. Mereka terkesiap melihat kami saling kejar-kejaran.
Sayangnya, aku sudah pernah berceritera kepada kalian: bahwa kadang, kelinci berlari lebih cepat daripada harimau yang akan memangsanya, bukan? Belum sampai dua menit kami berlari, tiba-tiba mendadak aku merasakan sesak di dadaku. Aku merasa kesulitan bernapas. Kuremat dadaku—membuat seragamku kumal seketika. Langkah lariku melaun. Sesak napas membuatku merasa pening seketika. Kuhentikan langkahku. Kurasakan, hidungku meneteskan darah. Aku mimisan. Mereka menetes-netes ke lantai linoleum koridor. Pandangan mataku memudar. Semua menjadi kabur. Aku tidak menyangka, symptom ini lebih cepat datangnya daripada yang aku duga.
Samar-samar kulihat Darell menyadari adanya kesalahan yang terjadi pada diriku. Ia sudah tidak asing dengan gejala-gejala ini. Ia berhenti dan berlari menuju ke arahku. Aku pun demikian. Sadar bahwa sebentar lagi, aku akan… pingsan.
Oh…, tidak lagi…
.
.
.
.
.
[Bersambung.]
Setelah aku banyak bercerita tentang diriku sebelumnya, aku rasa pada episode inilah inti dari cerita ini akan dimulai. Tentang apa yang sebenarnya ingin aku ceriterakan kepada kalian semua. Aku yakin, kalian tidak akan menyukainya. Aku rasa begitu.
Samar-samar kucium bau pengar yang membakar hidungku. Tidak membutuhkan waktu lama untuk menyadari bahwa aku berada di salah satu ruang inap rumah sakit. Kubuka kedua mataku. Kurasakan kepalaku masih pening. Kukerjapkan mataku untuk memperjelas pandanganku yang masih sayup. Nampak aku terbaring di salah satu ranjang ruang inap.
Kuamati sekeliling. Kulihat dinding tembok berwarna toska. Selaras dengan langit-langitnya yang berwarna dasar putih. Sebuah televisi tabung berada di tengah-tengah ruangan—diletakkan pada sebuah meja kayu coklat tua yang di pernis mengkilat. Nakas kecil dua laci terpajang di sebelah kanan ranjangku. Sofa berwarna krem pudar yang hanya mampu menampung dua orang dewasa, terpajang rapi di sebelah kiri ranjangku, ditata menghadap ke arahku. Sebuah tirai putih berpola daun ek berwarna oranye menghalangi pandanganku untuk melihat bagian kanan ruang inap ini.
Perlahan aku bangun dan menyibak tirai tersebut tanpa meninggalkan ranjangku. Kini, kulihat ada satu ranjang lain di sisi kananku. Hanya ada dua ranjang di dalam ruangan ini. Aku berada di ruang inap ganda rupa-rupanya. Itu menyebalkan, aku rasa. Namun biarlah, ranjang itu belum ada yang menempati. Aku sendirian di ruang inap ganda ini.
Di ujung ruangan, terdapat satu jendela kaca berbentuk kotak dengan lengkung kayu berupa setengah lingkaran pada bagian atas jendela tersebut. Jendela itu terbuka—membuat sirkulasi udara menjadi lebih baik di dalam sini. Sangat menyebalkan, tidak ada pendingin udara di sini. Dari tempatku duduk, aku bisa mendengar hingar-bingar kendaraan yang merayap di jalan raya. Suaranya masuk melalui jendela itu.
Di bagian tembok ruang yang berjendela tadi, tepatnya di bagian pojoknya, terdapat satu pot tanaman Lidah Mertua (Sansevieria trifasciata). Tanaman sukulen ini memang kerap di tempatkan di dalam ruangan karena hanya membutuhkan sedikit air dan paparan matahari saja untuk hidup. Pun ia mempunyai manfaat untuk menyaring udara di dalam ruangan—ia mampu menyerap udara kotor.
Terdapat sofa yang sama di sebelah kanan ranjang lainnya itu. Sofa itu menghadap ke arahnya.
Pintu terbuka, gerendel pintunya berdentang kecil. Rupanya itu adalah Mom. Ia tidak sendirian, seorang dokter laki-laki berusia paruh baya bersamanya.
“Mom, you came,” sapaku lemah.
“Yes, honey. Bagaimana perasaanmu, Shann?” tanya Mom.
“Better,” jawabku singkat.
“Baik, ada yang ingin engkau jelaskan kepada Mom, Nak?” tanyanya. Ia sudah tahu bahwa aku membuat kesalahan secara sembunyi-sembunyi—melanggar beberapa pantangan yang menjadi kontra terhadap tubuhku sendiri. Mom menuntut kejujuran dariku.
“Aku terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis, Mom,” jawabku lesu. Tidak ada gunanya berbohong.
“You knew you have made a mistake, Shann?” hardik Mom.
“Sorry,” kataku. Menyesal.
“Well, good news. Engkau harus dirawat di sini selama beberapa hari ke depan, Nak. Something has gone wrong inside your body,” jelas Mom. Aku terkesiap.
“Oh great,” keluhku. “What’s wrong with me? How bad it is?” tanyaku.
Mom tidak segera menjelaskan apa yang salah dengan tubuhku. Aku tahu bahwa sedari dulu, daya tahan tubuh dan staminaku memang lemah. Namun, mendengar nada penuturan Mom, mengisyaratkan ada hal lain yang salah di dalam tubuhku. Ia memandang dokter paruh baya itu, meminta bantuan untuk menjelaskan.
“Baiklah, Shann, engkau menderita hiperglikemia akut. Kadar gula dalam darahmu sedikit lebih tinggi daripada biasanya. Tubuhmu tidak mampu memproduksi hormon insulin secara normal. Kami perlu memastikan, apakah pankreasmu bermasalah? Dan itu membutuhkan waktu beberapa hari untuk mendiagnosa. Kami khawatir, itu gejala diabetes. Namun jangan risau, itu jarang terjadi pada anak,” jelas dokter paruh baya tersebut.
Alih-alih mendengarkan penjelasan dokter itu, aku malah asyik memperhatikan pin nama dokter itu yang berbentuk persegi panjang—tertulis dr. Carlos Henderson di sana.
“Baiklah, selama beberapa hari ke depan, kami akan menyuntikkan insulin pada tubuhmu. Untuk permulaan, dua kali satu hari. Setiap pagi sesudah makan, dan malam sebelum tidur, Shann,” tambahnya, dan itu membuatku terkesiap—disuntik.
“Oh no no no, great! No injection!” tukasku. “Mom,” gumamku mengiba. Aku selalu takut dengan yang namanya jarum suntik. Apapun selain itu.
“It’s okay, honey. It’s just a tiny shot,” Mom mencoba menenangkan.
“Ergh, I said NO!” geramku.
“Show your responsibility, Shann. Itu salahmu sendiri karena tidak pernah mau mendengarkan,” Mom bersikeras. “Tidak apa, Dok. Ia akan berubah pikiran,” tambahnya ke Dokter Carlos.
“Ergh…” erangku. “Mom, bisa pindahkan aku ke ruangan lain? Aku tidak suka di sini, ini ruang inap ganda,” keluhku.
“Perawat di sekolahmu membawamu ke sini, Shann. Tidak ada pilihan lain, semua ruangan di rumah sakit ini sudah penuh. Selain membuat khawatir karena engkau pingsan jauh lebih lama daripada sebelumnya, engkau sudah banyak merepotkan sekolah. Terimalah konsekuensi dari perbuatanmu,” tukas Mom.
Kuamati jam dinding bundar yang tergantung di atas televisi tabung. Jarum jam menunjukkan waktu siang hari. Aku rasa, sekolah sudah usai. Mom benar, aku pingsan jauh lebih lama daripada biasanya.
“Ergh, great!” keluhku kesal.
“Baiklah, banyak-banyaklah istirahat. Suster akan memantau perkembanganmu setiap tiga jam sekali. Mari,” kata dokter tersebut.
“I’ll be right back,” Mom berlalu mengikuti dokter tersebut. Mungkin untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan rawat inapku selama beberapa hari ke depan.
Ruangan kembali lenggang. Kurebahkan punggungku dengan keras. Kudenguskan napasku. Kesal sendiri karena kebodohanku. Mungkin jika semalam aku tidak menyantap sereal secara diam-diam, dan tidak mengambil granola bar tadi pagi, aku akan baik-baik saja. Tentunya, pasti harimau akan lebih cepat dari kelinci yang berlari terbirit-birit. Aku semakin membenci Riley. Sialan, dia itu! Ia pasti mentertawakanku yang pingsan karena berusaha mengejarnya tadi pagi. Aku akan membalasnya besok!
Bagaimana jadinya kelompok perundung kecil itu tanpa kehadiranku selama beberapa hari ke depan? Aku tidak akan membiarkan Claire direbut begitu saja oleh Riley. Jangan salah sangka, aku tidak akan menjadikannya pacar. Tidak. Aku hanya tidak suka jika apa yang menjadi milik kelas kami, dimiliki oleh kelompok kelas lain. Selama ketidakhadiranku, aku hanya bisa mengandalkan Darell sebagai beta di dalam kelompok perundung kecil kami. Aku yakin, ia bisa diandalkan.
Kuraih modulator saluran televisi yang tergeletak di atas nakas dua laci di sebelah kananku. Aku nyalakan televisi tabung yang terpajang dia tas meja kayu coklat. Lalu kutekan-tekan tombol modulator saluran televisi itu. Oh bagus sekali, hanya ada 15 saluran televisi nasional dan lokal, tidak ada saluran luar. Benar-benar membosankan. Aku tidak bisa menonton Disney Channel, saluran favoritku selama beberapa hari ke depan. Benar-benar akan sangat membosankan. Ruang inap ini seperti penjara bagiku. Aku tidak diperbolehkan kemana-mana kecuali ke toilet, mereka membiarkanku membusuk di sini dengan segala kebosanan yang ada.
Kumatikan televisi tabung itu. Bunyi plik pelan terdengar samar seiring dengan gelapnya layar televisi itu. Kulempar malas modulator saluran televisi itu ke ranjang kasurku.
Tidak menunggu lama, Mom sudah kembali.
“Shann, Mom akan pulang untuk mengambil baju dan beberapa barang lainnya yang diperlukan untukmu. Dad akan tiba sebentar lagi. Jadilah anak yang baik selama Mom tidak ada, Okay? Dan itu perintah,” kata Mom.
“Can you get my iPad?” pintaku mengiba.
“Sure,” sahut Mom.
“And my pillow as well?” pintaku.
“Sure, Shanny Shanny Boo,” kata Mom seraya memutar kedua bola matanya.
“Oh, bring me Brian please, I need it,” kataku.
“No pets are allowed inside the hospital. You knew it so well, Shann,” Mom menghela napas.
Setelah kepulangan Mom, aku sudah kembali di rundung kebosanan.
.
.
.
.
.
[Bersambung.]